Sinisme Pelancong dan Ironi Pariwisata
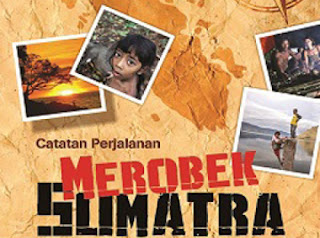
Oleh Deddy Arsya
Cerita-cerita perjalanan menjadi populer kembali dewasa ini. Majalah-majalah traveling berlahiran. Rubrik jalan-jalan hadir setiap akhir pekan nyaris pada semua suratkabar. Buku-buku dengan genre ini dengan gampang dapat ditemui pada rak-rak toko buku. Perkembangan ini tampak paralel dengan promosi pariwisata yang sedang hingar-bingar disorakkan pemerintah nyaris di seluruh daerah dan kota, bahkan dalam skala bangsa.
Merobek Sumatra karya Fatris MF ini (diterbitkan penerbit Serambi, April 2015) berpotensi menjadi bagian dari gejala massif tersebut. Buku ini berhasil selamat hanya karena pandangannya yang sinis terhadap pariwisata dan bagaimana penulisnya mengolah ironi hayat-sosial-kultural dunia wisata menjadi terasa tragik ke hadirat pembaca.
Pertalian dengan Penjajahan dan Stimulus Pariwisata Modern
Buku cerita perjalanan setidak-tidaknya telah ada sejak abad ke-16 (bahkan mungkin lebih tua dari itu). Genre ini pada satu sisi punya ikatan erat dengan proses penjajahan: teks-teks perjalanan menginspirasi penjelajah Eropa awal menemukan dunia baru. Tetapi di sisi yang berbeda, teks-teks ini juga punya hubungan dengan kepentingan pariwisata: sejarah pariwisata modern konon mengambil bentuk promosi paling awal melalui kisah-kisah perjalanan.
Ahmad Sunjaya, dalam sebuah artikel penutup untuk buku yang ditulis Clockener Brousson, menyebutkan bahwa ada dua jenis teks-teks perjalanan yang telah muncul pada abad ke-16 (khususnya di Eropa): scheepjournalen (catatan perjalanan kapal) dan reisdagboek (catatan kejadian sehari-hari). Pada abad ke-17, jenis yang pertama merupakan salah satu bahan bacaan yang paling disukai. Isinya menyajikan petualangan pelayaran di tengah alam liar yang eksotik di Hindia. Ahmad Sunjaya menulis bahwa catatan kategori ini misalnya ditulis pelaut Wilem Bbrantsz Bontekoe, pendeta Francois Valentijn, Goerg Evetard Rumphius, Nicolaus de Graaff dan ahli botani Franz Wilhelm Junghun.
Sementara jenis yang kedua mulai populer pada abad ke-18. Di mana gambaran kehidupan keseharian masyarakat yang didatangi mengambil tempat yang lebih signifikan. Pencatatan tidak lagi hanya dilakukan oleh mereka yang ikut dalam ekspedisi zaman pelayaran, tetapi telah meluas kepada pegawai-pegawai Eropa yang telah menetap di tanah jajahan, pejabat-pejabat militer maupun sipil kolonial, para ilmuwan, dan termasuk pihak pers. Pada periode ini, pembicaraan telah dilakukan para penjelajah dan pelancong mengenai penduduk pribumi yang mereka kunjungi. Mulai dari pengidentifikasian watak, mentalitas, tabiat, hingga segala sesuatu yang berkaitan dengan adat-istiadat setempat.
Catatan-catatan perjalanan tersebut menjadi buku pegangan para petualang sebelum menjejakkan kaki di tempat tujuannya. Di sisi lain, mengutip Frances Gouda, catatan-catatan tersebut juga menggugah minat para orang kaya di Eropa untuk datang. Apalagi bagi mereka yang memiliki jiwa petualangan dan memiliki banyak modal. Untuk itu, pariwisata adalah imbas lain dari kehadiran buku-buku tersebut.
Di Indonesia, buku-buku cerita perjalanan secara lebih semarak hadir belakangan, yaitu pada awal abad ke-20 ketika dunia cetak sudah menjadi familiar dalam masyarakat kita. Sekalipun tidak dipungkiri mungkin saja telah ada buku cerita perjalanan yang ditulis pribumi lebih tua dari masa tersebut. Biasanya, cerita perjalanan ditulis secara berseri di suratkabar untuk kemudian dikumpulkan dan dicetak luas dalam bentuk buku. Ada beberapa penulis cerita perjalanan yang terkenal dari kalangan Indonesia: Adinegoro, Parada Harahap, Muhammad Radjab, dan lainnya.
Gambaran Mooi Indie
Gambaran dalam buku-buku perjalanan klasik (khususnya Eropa) adalah gambaran kemolekan alam. Gambaran itu mengeras dalam pikiran orang-orang Eropa selama berabad-abad sebagai dasar pengetahuan mereka tentang negeri-negeri di Timur. Keberbedaan dengan mereka, bagi ‘turis Barat’, tampak sebagai eksotisme dunia Timur yang menantang. Gambaran tersebut bahkan masih ada dan bertahan sampai hari ini.
Denis Lombard, sejarawan Prancis yang hadir pada abad kita sekarang, menuliskan dalam bukunya yang terkenal, Nusa Jawa dan Silang Budaya: “Lebih dari satu abad kemudian, citra Kepulauan Indonesia pada kami masih sering sekali merupakan citra eksotisme. Mooi Indie, Hindia yang molek, sebagaimana kepulauan itu disebutkan pada zaman penjajahan, masih tetap ada.” Seakan-akan, tidak ada perubahan berarti yang dialami masyarakat di dunia Timur selama berabad-abad. Masyakaratnya, memakai bahasa Lombard lagi, “beku dalam keindahan berwarna-warni”.
Citra itu dilanjutkan dan diteruskan oleh orang-orang bangsa Indonesia sendiri secara sadar atau tidak dewasa ini (bahkan termasuk pada penulis cerita perjalanan paling awal dari kalangan bumiputra yang sebelumnya disebutkan). Dewasa ini, beberapa kebijakan pariwisata, misalnya, menginginkan masyarakat—yang dijadikannya objek—sedapat mungkin menjadi kuno dan bersetia dengan kekunoannya. Pandangan serupa itu muncul karena anggapan bahwa apa yang paling kuno dari objek wisata akan laku untuk mendatangkan turis-turis dari dunia modern. Kecendrungan ini juga dilakukan oleh para traveler atau para ‘jurnalis pelancongan’ (meminjam terma Parada Harahap dalam bukunya Dari Pantai ke Pantai).
Lalu catatan-catatan perjalanan yang dihasilkan menjadi a-historis, terbebas dari waktu; seakan-akan tidak ada yang berubah dari masyarakat yang dikunjungi dan dibicarakannya. Hal tersebut bisa jadi benar karena fokus pandangan (dari balik kacamata hitam) mereka yang hanya terkagum-kagum pada alam yang indah dan eksotik, tetapi melupakan bagaimana masyarakat di sekitar tempat-tempat wisata itu bergelut dengan berbagai dinamika sosial dan kulturalnya sendiri.
Sinisme dan Ironi Pariwisata
Buku Merobek Sumatra karya Fatris MF ini tampak berada pada jalur yang lebih berbeda. Inilah buku tentang perjalanan ke tempat-tempat wisata’ yang nyaris sinis pada pariwisata. Destinasi-destinasi wisata yang elok dipandang dengan sorot mata curiga, dengan sudut mata yang tajam. Nyaris tidak terdapat anasir ‘terkagum-kagum’ a la pelancong dari dunia urban, misalnya, melihat keeksotikan suku-suku pedalaman dan kampung-kampung terkurung hutan belantara Sumatera.
Tampak yang dibicarakan penulis buku ini bukan lagi berpusar pada tempat-tempat wisata, tetapi bagaimana pergulatan sosial dan kultural masyarakat di sekitarnya merespon kehadiran pariwisata untuk kehidupan mereka. Bagaimana masyarakat di sekitarnya dilamun arus kebijakan pariwisata yang hendak menjadikan mereka objek. Bagaimana masyarakat tersebut berubah dengan caranya sendiri—yang pada beberapa sisi seakan menentang kebijakan pariwisata yang ingin membuat mereka tetap ‘lestari’.
Buku ini justru tampak menolak pemikiran mainstream dunia pariwisata yang hendak ‘melestarikan’ yang tidak mungkin lestari itu. Penulis buku ini mengatakan, bagaimana mungkin manusia bisa diharapakan untuk tetap “bersetia pada kekunoannya”, pada “kebekuannya”, sementara pada hakikatnya pada masyarakat-manusia toh “perubahanlah yang abadi”?
Lihat misalnya catatan perjalanan penulis buku ini ke Mentawai. Fokus artikel tersebut adalah tentang seorang remaja Mentawai, Aman Lepon, yang tidak mau lagi menjadi Sikerei (pemimpin adat), tidak bersedia lagi tinggal di huma dan ditato (sebagaimana tradisi kuno), tetapi lebih memilih menjadi guru (pegawai negeri) untuk dunia modern.
Aneh memang, sebuah buku tentang berwisata tidak memokuskan tulisannya pada tempat-tempat wisata. Nyaris, pembicaraan tentang alam Mentawai yang indah, ombak besar yang menjadi incaran para peselancar yang terkenal di dunia itu, atau dunia bawah laut dengan turumbu karang yang menawan, hanya disinggung ringkas saja.
Si penulis, memang, tengah menikmati keindahan itu semua dalam pelancongannya. Dia turut mandi di laut Mentawai, surfing, snokling, atau berbiduk-biduk di muara yang eksotik dengan kaki-kaki bakau yang panjang. Tetapi, dalam ‘aktivitas berwisatanya itu’ bayang-bayang tragik dari hutan Mentawai yang habis, hewan-hewan endemik pulau itu yang lenyap, masih terus mengganggu upayanya untuk menikmati destinasi-destinasi wisata. Bahkan, suara Aman Lepon (sebagai representasi dari persoalan sosial-kultural Mentawai hari ini) masih terngiang-ngiang di telinganya sekalipun tengah snokling di pantai indah Siberut yang berpasir putih dan langsung berhadapan dengan Samudra Hindia itu. “Tidakkah seorang Sikerei, juga adalah guru—guru bagi kaummu!” tulis Fatris MF, seperti berbisik kepada Aman Lepon.
Lihat pula ketika penulis buku ini melancong ke Jambi. Dia menyaksikan candi kuno Muara Jambi yang gagah, berperahu-perahu di telaga purba tempat berabad-abad yang silam putri dan pangeran kerajaan Malayu mungkin melakukan hal yang sama. Dia melihat pohon bodhi yang tinggi besar tidak jauh dari candi itu yang dianggap ditanam langsung oleh sang Budha. Dia menyaksikan patung-patung para Bodhisatva dan mendengarkan narasi-narasi yang menakjubkan tentang mereka di sebuah museum sejarah dalam kompleks yang sama.
Tapi bukan semua itu yang justru hendak ditekankan sang pelancong kepada pembacanya. Catatannya justru memberi porsi yang lebih besar kepada gambaran tentang bagaimana Batanghari rusak akibat penambangan emas dan batubara; tongkang-tongkang besar mengangkut kayu-kayu gelondongan dari hulu; potret miskin rakyat setempat di pinggir-pinggir Batanghari dengan rumah-rumah kayu mereka yang kumuh. Sementara jalan raya dipenuhi truk-truk pengangkut sawit; kotanya hiruk-pikuk oleh dunia malam dan geliat pembangunan mall dan plaza.
Bagaimana mungkin tempat-tempat wisata yang indah dan eksotik dapat dinikmati jika di sekelilingnya kemiskinan merebak bagai kurap di kerampang; lingkungan alam rusak; dan pemilik modal berkuasa atas hayat orang banyak?
Alam yang indah itu bukan lagi ‘ibu’ seperti dalam pemahaman klasik. Tetapi, mengutip Fancis Bacon, alam telah menjadi ‘objek eksploitasi’ bagi keberkuasaan manusia. Begitu juga dengan Pariwisata, dia telah menjadi milik sedikit orang yang mengeruk keuntungan darinya. Pariwisata, dengan begitu, memperlihatkan wujudnya yang paradoksal. Pola serupa itu nyaris jamak ditemukan dalam artikel-artikel tentang Sumatera yang terkumpul dalam buku ini. Pola yang membuat dirinya berbeda dari buku catatan perjalanan pada umumnya.
Padang, 2015
(Padang Ekspres, 3 Mei 2015)



Comments
Post a Comment